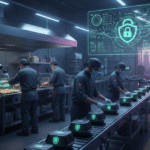Teknologipangan.umsida.ac.id – Di rak minimarket hingga etalase toko daring, klaim “rendah gula”, “tanpa gula tambahan”, atau “menggunakan gula alami” kini semakin mudah ditemukan. Produk minuman, biskuit, yogurt, hingga camilan sehat berlomba-lomba menawarkan versi “lebih aman” bagi konsumen yang khawatir akan diabetes, obesitas, dan penyakit metabolik. Salah satu strategi yang paling sering digunakan industri adalah mengganti gula pasir dengan berbagai jenis gula alternatif, seperti stevia, eritritol, sorbitol, maupun gula kelapa.
Sebagai mahasiswa Teknologi Pangan, fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam. Apakah penggunaan gula alternatif benar-benar memberikan manfaat kesehatan? Atau justru hanya menjadi strategi pemasaran yang memanfaatkan ketakutan konsumen terhadap gula? Untuk menjawabnya, perlu pemahaman tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dari sudut pandang ilmu pangan, teknologi formulasi, dan regulasi.
Mengapa Gula Alternatif Menjadi Tren?

Gula pasir (sukrosa) selama bertahun-tahun menjadi pemanis utama dalam produk pangan. Namun, meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular mendorong perubahan perilaku konsumsi. Organisasi kesehatan dunia (WHO) bahkan merekomendasikan pembatasan asupan gula bebas untuk menekan risiko kesehatan jangka panjang.
Kondisi ini mendorong industri pangan mencari pemanis lain yang memiliki nilai kalori lebih rendah, indeks glikemik rendah, atau tingkat kemanisan lebih tinggi sehingga penggunaannya bisa diminimalkan. Di sinilah gula alternatif mendapat panggung utama. Dari sudut pandang industri, gula alternatif bukan hanya solusi teknologis, tetapi juga alat komunikasi pemasaran yang efektif.
Mengenal Jenis-Jenis Gula Alternatif
Dalam ilmu teknologi pangan, gula alternatif dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, pemanis intensitas tinggi seperti stevia dan sukralosa. Stevia, misalnya, berasal dari tanaman Stevia rebaudiana dan memiliki tingkat kemanisan hingga 200–300 kali sukrosa. Karena sangat manis, penggunaannya hanya sedikit dan hampir tidak menyumbang kalori.
Kedua, poliol atau gula alkohol, seperti eritritol, xylitol, dan sorbitol. Pemanis jenis ini memiliki struktur kimia berbeda dari sukrosa dan dicerna lebih lambat oleh tubuh, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Namun, konsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek samping seperti kembung atau diare.
Ketiga, gula alami non-sukrosa, seperti gula kelapa atau gula aren. Meski sering dianggap lebih sehat karena “alami”, secara kimiawi gula ini tetap mengandung karbohidrat sederhana dan kalori yang relatif tinggi.
Bagi mahasiswa Teknologi Pangan, penting untuk memahami bahwa istilah “alami” atau “alternatif” tidak selalu identik dengan “bebas risiko”.
Tantangan Formulasi: Tidak Sekadar Manis

Mengganti gula pasir dalam produk pangan bukan perkara mudah. Dalam teknologi pangan, gula tidak hanya berfungsi sebagai pemanis, tetapi juga berperan dalam tekstur, warna, stabilitas, dan daya awet produk. Pada produk bakery, misalnya, gula berperan dalam reaksi Maillard dan karamelisasi yang memengaruhi warna dan aroma.
Ketika gula diganti dengan stevia atau eritritol, produsen sering menghadapi tantangan sensorik. Stevia dikenal memiliki aftertaste pahit, sementara eritritol dapat memberikan sensasi dingin di mulut. Dari sudut pandang teknologi pangan, hal ini memerlukan strategi formulasi lanjutan, seperti blending beberapa pemanis, penggunaan flavor masker, atau penyesuaian proses pengolahan.
Di sinilah peran ahli dan mahasiswa teknologi pangan menjadi krusial. Inovasi pemanis bukan hanya soal menurunkan kalori, tetapi juga menjaga akseptabilitas konsumen.
Aspek Kesehatan: Lebih Aman, tapi Bukan Tanpa Batas
Secara umum, gula alternatif telah melalui uji keamanan dan memiliki nilai Acceptable Daily Intake (ADI). Artinya, selama dikonsumsi dalam batas wajar, pemanis ini aman. Namun, sebagai mahasiswa teknologi pangan, kita perlu bersikap kritis terhadap narasi “bebas gula berarti bebas masalah”.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pemanis non-nutritif dalam jangka panjang dapat memengaruhi persepsi rasa manis dan pola makan. Konsumen bisa terbiasa dengan rasa sangat manis, sehingga tetap sulit mengurangi ketergantungan terhadap produk manis. Selain itu, klaim “rendah gula” sering kali membuat konsumen merasa aman untuk mengonsumsi lebih banyak, yang justru berpotensi meningkatkan asupan kalori total.
Regulasi dan Klaim Pangan: Area Abu-Abu
Di Indonesia, klaim seperti “rendah gula” atau “tanpa gula tambahan” diatur oleh BPOM. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat celah interpretasi. Produk bisa saja tidak menggunakan sukrosa, tetapi tetap mengandung pemanis lain dalam jumlah signifikan.
Bagi mahasiswa teknologi pangan, pemahaman regulasi ini penting agar tidak terjebak pada narasi pemasaran semata. Edukasi konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara regulator, industri, dan akademisi.
Antara Inovasi dan Ilusi Marketing
Gula alternatif pada dasarnya adalah hasil inovasi teknologi pangan yang memiliki potensi besar untuk mendukung pola makan lebih sehat. Namun, manfaat tersebut hanya bisa dirasakan jika digunakan secara tepat, transparan, dan disertai edukasi yang memadai.
Dari sudut pandang mahasiswa Teknologi Pangan, fenomena gula alternatif mengajarkan bahwa pangan bukan hanya soal rasa dan gizi, tetapi juga tentang etika industri, literasi konsumen, dan tanggung jawab ilmiah. Tantangan ke depan bukan sekadar menciptakan produk rendah gula, melainkan bagaimana memastikan inovasi tersebut benar-benar memberikan dampak positif, bukan sekadar ilusi kesehatan yang dibungkus label menarik.
Penulis: Enky Okta Wijaya